 Ada ungkapan seperti ini: “dia itu orang kafir" ; "orang kafir itu tidak pantas menjadi pemimpin" ; "orang-orang kafir itu tidak akan masuk syurrga”... dan bla..bla...bla...lainnya
Ada ungkapan seperti ini: “dia itu orang kafir" ; "orang kafir itu tidak pantas menjadi pemimpin" ; "orang-orang kafir itu tidak akan masuk syurrga”... dan bla..bla...bla...lainnya
Dalam konteks bernegara, kalimat-kalimat di atas sesungguhnya merupakan sebuah kecurigaan mendalam terhadap kelompok lain. Lebih tepatnya kata ini adalah “penistaan” terhadap agama lain.
Akhir-akhir ini, memang istilah “kafir” atau mengafirkan orang, mulai mewabah lagi di medan merdeka ini. Beberapa Pemuka Agama yang justru menjadi panutan umat, muncul bersama klaim-klaim arogansinya, seraya menuduh orang yang tidak sepaham dengan sebutan “orang kafir”.
Mereka muncul mendakwahkan kebenaran namun seakan-akan menganggap dirinya sendiri paling benar, tersuci dan paling tak berdosa dibanding dengan orang lain, sekaligus dari ajaran yang ia dakwahkan tersebut! Dan celakanya lagi, mereka tidak menyadari bahwa dengan melakukan hal seperti itu, sesungguhnya mereka sudah menurunkan derajad kesucian Allah SWT.
Makna "Kafir" Yang Sesungguhnya
Jika berkenan, mari kita sejenak mendalami makna dari istilah 'kafir' ini secara cermat dan tidak membabibuta. Mungkin kata ini sejak kecil sudah melekat pada kita. Dan makna yang tidak tepat ini turun temurun diwariskan dari generasi ke generasi, yang pada akhirnya kita menerimanya dengan taken for granted saja, tanpa harus memeriksa lagi kebenaran makna yang sesungguhnya terkandung di dalamnya.
Dan seandainya mereka-mereka yang sering dengan sombongnya menggunakan kata ini untuk menjustifikasi orang lain, mau sedikit menjadi cerdas dengan membuka Al-Quran, maka tentu mereka akan menemukan makna qur’aniyah dari kata ‘kafir’ ini yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perbedaan agama secara langsung.
Ya, makna qur’aniyyah dari istilah ‘orang kafir’ bisa kita temukan di dalam surat Al-Kahfi ayat 100 dan 101, sebagai berikut:

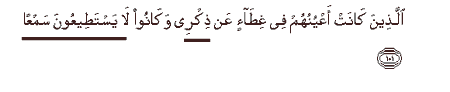
Q.S. 18:100, “dan Kami tampakkan Jahannam pada hari itu kepada orang-orang kafir (Al-Kafiriin) dengan jelas.”
Q.S. 18:101, “yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari ‘zikri’ (diterjemahkan di terjemahan qur’an bahasa Indonesia dengan kata ‘memperhatikan’) terhadap tanda-tanda kebesaran-Ku, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar.”
Dari dua ayat di atas, kita bisa menemukan definisi qur’aniyyah dari kata ‘kafir’ secara jelas, bahwa Al-Kafiriin atau orang-orang kafir adalah mereka yang matanya tertutup dari ‘zikri’ terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, dan telinganya tidak sanggup mendengar.
Maka demikian, apakah orang yang kebetulan ketika lanjut usia ia menjadi tuli atau menjadi buta karena usia tua, apakah ia berarti ditakdirkan akan mati dalam keadaan kafir? Atau, jika seseorang kebetulan ditakdirkan tuli atau buta sejak lahir, apakah artinya ia ditakdirkan untuk hidup sebagai orang kafir? Sebab sama sekali bukan keinginannya untuk dilahirkan sebagai orang buta atau tuli. Apakah Allah menakdrkannya kafir karena kebetulan lahir sebagai orang tuli atau buta?
Jawabannya adalah tidak! Semua orang, termasuk mereka yang buta atau tuli, diberikan Tuhan kesempatan untuk mati kelak dalam keadaan diridhoi-Nya. Jika demikian, mata dan telinga mana yang tertutup? Jawabannya bisa kita dapatkan pada Al-Qur’an surat Al-Hajj (22) ayat 46.
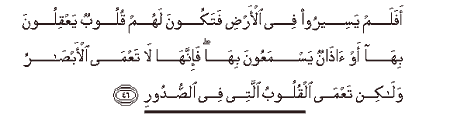
Q.S. 22:46, “Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah qalb-qalb mereka (quluubun) yang ada di dalam dada.”
Dari definisi Qur’an di atas maka jelaslah bahwa yang disebut ‘kafir’ bukanlah orang yang berbeda agama, tetapi mereka yang mata dan telinga qalb di dalam dadanya tidak berfungsi. Asal kata ‘kafir’ dan ‘kufur’ adalah ‘kafara’ yang artinya ‘tertutup’ (kata ini diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi ‘cover’ artinya penutup). Artinya bahwa ‘kafir’ adalah orang yang masih tertutup dari ‘Al-Haqq’ (kebenaran mutlak).
Mata dan telinga yang di dalam dada, maksudnya adalah mata dan telinga yang adanya bukan pada level jasad kita, tapi lebih dalam lagi. Mata dan telinga yang dimaksud adalah mata dan telinga yang ada dalam qalb kita, dalam dada/shuduur, yang ada pada level jiwa (nafs). Shuduur artinya ‘dada spiritual’, sebagaimana hati yang biasa kita kenal bukanlah liver maupun jantung, tapi lebih kepada aspek afektif manusia yaitu hati nurani (‘hati spiritual’).
Nah pertanyaannya, jiwa atau nafs yang mana? Tentu kita mengetahui bahwa ada tiga unsur yang dipersatukan dalam membentuk kesatuan manusia yang hidup, yaitu Ruh, Nafs (jiwa), dan Jasad. Jiwa inilah, yang di dalam ajaran Muslim diabadikan dalam Q.S. 7:172, yang dahulu sekali di sumpah di hadapan Allah untuk menjadi saksi (syahid, perhatikan kata bahasa arabnya: syahidna, kami bersaksi) mengenai siapakah Rabb mereka.
Selanjutya, Fahmi Huwaidi (1999) dalam bukunya "Muwathinun La Dzimmiyyun" menyatakan bahwa sebenarnya istilah “kafir dzimmy” bukanlah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Islam. Ia sudah ada sejak kabilah-kabilah Arab mulai bersekutu satu dengan yang lainnya. Islam hanya melanjutkan apa yang sudah berlaku saja. Begitu pula dengan istilah “jizyah”, yang sudah dikenal bahkan sejak masa Kisra di daerah Persia. Islam, lagi-lagi hanya meneruskan sistem tersebut.
Maka dengan demikian, upaya penyesuaian sistem tersebut di masa sekarang sangat dimungkinkan. Fahmi menghadirkan 4 (empat) argumen untuk menguatkan ide tersebut:
Pertama, prinsip umum bahwa umat manusia (apapun agamanya) telah dimuliakan oleh Allah (Al-Isra’: 70).
Kedua, Al Qur’an mendorong umat Islam agar berlaku baik dan adil bagi non-Muslim yang tidak memerangi mereka (Al-Mumtahinah: 8). Diantara sikap adil tersebut adalah memberi hak dan kewajiban yang sama.
Ketiga, esensi dari perlindungan Rasulullah Saw pada kafir dzimmy. Rasul dalam hal ini ‘pasang badan’ untuk golongan ini. Menunjukkan mereka memiliki kehormatan yang sama.
Keempat, Piagam Madinah yang secara tersurat dan tersirat menempatkan Yahudi-Nasrani sebagai warga “negara” Madinah.
Empat argumen Fahmi di atas merupakan bentuk “ijtihad”, dalam artian bahwa pintu ijtihad tidaklah tertutup. Sebagaimana kekhalifahan Turki Utsmani (Ottoman) yang berada pada kekhalifahan terakhir pada tahun 1876 sudah menghapus istilah ‘dzimmy’ ini menjadi “muwathin” (warga negara), yang meskipun penghapusan ini termasuk ijtihad politik, namun substansi utamanya adalah agar sesuai dengan perkembangan zaman.
Nah, bagaimana dengan konteks sekarang? Kekhalifahan Islam sudah tidak ada lagi di muka bumi. Negara-negara Islam sudah berdiri sendiri-sendiri. Dalam artian mereka tidak lagi terikat dengan kekhalifahan. Maka dengan sendirinya istilah “kafir dzimmy” bersama dengan segala aturan-aturan tentangnya, secara otomatis gugur bersamaan dengan hilangnya sistem kekhalifahan. Kendatipun istilah “kafir dzimmy” dapat di ubah menjadi "muwathin" (warga negara) pada sistem pemerintahan Islam.
'Kafir' dalam Konteks Indonesia
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep “kafir” dalam konteksnya dengan negara Indonesia? Tentu saja di negara yang menganut sistem demokrasi, istilah kafir sangat-sangat tidak relevan. Indonesia tidak diperuntukkan untuk dikelola oleh kaum mayoritas Muslim saja. Sebab demokrasi di Indonesia memungkinkan siapa saja berhak mengambil peran politik.
Untuk itu, penggunaan kata “kafir” tidak dapat dibenarkan sama sekali di ruang publik Pancasilais. Sebab jika kata ini digunakan dengan harbabiruk (boleh di baca: “seenaknya”), maka bangsa Indonesia akan semakin berada di dalam krisis, di mana Agama akan dianggap sebagai stasiun akhir dari sebuah kultus yang harus dipaksakan kepada siapa saja, kapan sajam dan di mana saja, serta dengan cara apa saja. Dan ini sangat berbahaya.
Memang tak bisa dipungkiri bahwa dalam iklim demokrasi Indonesia sangatlah dimungkinkan bagi kelompok-kelompok agama mendukung satu sosok atau figur yang hanya mewakili agamanya saja. Hal ini lumrah dan sah-sah saja. Namun sekali lagi, penggunaan kata “kafir” atau kata “musyrik” misalnya, haruslah terbatas pada mimbar keagamaan saja (wilayah privat).
Istilah apapun yang digunakan untuk menyebutkan kelompok lain di luar agama yang kita anut, terbatas pada ranah agama itu sendiri. Sebab sekali lagi, dalam demokrasi tidak ada istilah kafir dan yang sejenis. Sebagaimana dalam konteks perpolitikan global, tidak kurang banyaknya pemimpin negara-bangsa yang juga beragama Muslim. Tapi pada kenyataannya, jauh panggang dari apinya. Muslim ataukah non-Muslim, sama sekali tidak menjamin kualitas kepemimpinan.
Tanpa tasbih, sorban, jubah, Presiden Soekarno dan Muhamad Hatta, misalnya, berhasil mengobarkan perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan NKRI. Mandela yang bukan Muslim, berjaya dan dihormati di Afrika. Gandhi yang Hindu, juga menjadi kecintaan di negara India. Bahkan Chavez yang Katolik, dipuja-puji di Venezuela, dll.
Agama dan ajarannya tidak bisa dijadikan sandaran pengelolaan kehidupan bernegara yang di dalamnya terdiri dari berbagai etnis, budaya dan agama. Tetapi bukan berarti para pemeluknya harus kehilangan kewarasan berpikir, dan kejernihan hati dalam memahami doktrinnya masing-masing.
Kita perlu melihat ke belakang karena kehancuran sebuah bangsa di masa lalu, cenderung terjadi akibat agama-agama yang selalu ditunggangi para pegiat politik dengan seperangkat ambisinya untuk berkuasa. Dan nyaris semua agama dunia pada era sekarang ini—termasuk NKRI—memiliki seperangkat riwayat kelam akibat kolaborasi ‘penguasa’ melalui lembaga agama ini.
Semua ayat suci yang sejatinya diturunkan Tuhan ke muka bumi, tak cukup hanya dijadikan korpus semata. Ia harus dipahami dengan arif dan bijaksana. Ya, keniscayaan seperti inilah yang selanjutnya menyita habis kehidupan para pembawa kebaikan dan pembawa keadilan untuk mengasihi dan menyayangi sesamanya pada setiap zaman ke zaman. Jauh di lubuk hati, mereka sadar dan paham betul, waktu pasti akan melindas. Maka tak ada pilihan lain kecuali hidup saling mengasihi bersama waktu yang berawal tapi tak berakhir. Jalan terbaik mewujudkan itu adalah, menjadi agen kebaikan dari waktu ke waktu untuk manusia dan makhluk Tuhan lainnya, demi menghadirkan kebaikan dan keadilan. Sebab dengan berbuat kebaikan itulah maka nama mereka dapat dikenang dan harum sepanjang masa. Hidup mereka pun abadi dalam sejarah manusia.
Mugkin kita masih ingat sosok Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (24 Januari 2017) pernah mengajukan keberatan atas sebutan “kafir” kepadanya. Ahok saat itu sempat mengatakan: "Saya keberatan saya disebut kafir. Saya percaya Yesus Tuhan saya bukan kafir. Saya berhak menjadi apa saja di negeri ini."
Ya, sesungguhnya kafir-mengkafirkan seseorang di alam demokrasi ini, adalah suatu kebodohan, sekaligus kedangkalan dalam berbangsa dan bernegara. Ini sebuah patologi! Tepatnya, penyakit di alam demokrasi.
Profesor Antropologi Budaya di King Fahd University of Petroleum and Minerals Arab Saudi, Sumanto al Qurtuby (2016), dalam artikelnya menyatakan bahwa, sesungguhnya status “kafir-sesat” sangat relatif-subyektif.
Kita bisa saja memandang sesat atas praktik keagamaan orang lain. Tetapi sadarkah kita bahwa orang lain itu juga bisa jadi memandang sesat terhadap praktik keagamaan yang kita lakukan. Jadi tidak ada label “kafir-sesat” yang bersifat “obyektif” dan “inheren”, karena faktanya apa yang kita anggap “benar” dan “legitimate” itu belum tentu dianggap “benar” dan “legitimate” di mata orang lain.
Sebagaimana sudah di bahas sebelumnya bahwa sesungguhnya makna kata “kafir” adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, jika saja kata ini muncul di depan publik Pancasilais yang menjunjung tinggi kesamaan hak dan kewajiban, lalu kemudian dilontarkan kepada umat Nasrani, maka sesungguhnya hal itu adalah sebuah penghinaan terhadap agama Kristen, yang harus diberikan sangsi tegas melalui ranah hukum yang berlaku di Republik tercinta ini. Pada saat yang sama juga merupakan arogansi yang mendahului penghakiman Tuhan.
Kristen bukan kafir! Sebab agama Kristen percaya kepada Allah YAHWEH, yakni Allah Abraham, Isak dan Yakub, bahkan Allah Ismail! Sebagaimana kitab Mazmur 33:12 menuliskan, “Berbahagialah bangsa yang Tuhannya adalah YAHWEH”.
Perlu ditegaskan bahwa Tuhan Alkitabiah bukan merupakan hasil suatu deskripsi manusia. Dia menyatakan Diri-Nya sendiri kepada Abraham, Yakub, Musa dan para Nabi, dan Dia turun ke dunia untuk memanifestasikan Diri-Nya sendiri secara badaniah dalam wujud pribadi Yesus dari Nazaret. Dimana Yesus berkata: “Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa” (Yohanes 14:9).
Jadi pada titik ini umat Kristen tidak menyusun konsep Tuhan Alkitabiah. Tuhan yang sendiri menyatakan DiriNya, yaitu HakikatNya, NamaNYa, KemuliaanNya, Hukum-hukumNya, PengadilanNya, KasihNya, dan KesucianNya. Jika semuanya itu disingkirkan melalui klaim-klaim sesat yang tidak terukur kebenarannya, maka berarti tidak ada maujud yang dinamakan Kristen!
Inilah yang harus dipahami agar kita tidak mengatakan kata “kafir” pada agama lain dengan seenaknya, sehingga tidak terperosok dalam klaim benar-salah.
Refleksi Bersama
Sebagaimana sudah ditekankan sebelumnya bahwa akhir-akhir ini kita kerapkali mendengarkan kata “kafir” yang keluar dari para Tokoh Agama dan pemeluk Islam radikal, baik di media sosial, melalui tulisan teks, maupun melalui video, dll. Pertanyaannya, siapakah manusia yang layak mengkafirkan orang lain di negara Pancasila ini?
Menurut UU No 40 tahun 2008, telah dinyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara dengan keberagaman. Tidak ada orang, kelompok, institusi yang berhak berlaku SARA, mengelompokkan orang hanya karena, suku, etnis, agama.
Berdasarkan UU di atas, jelaslah bahwa eksklusivitas dari satu kelompok agama tertentu, adalah melawan hukum di Indonesia. Indonesia negara besar yang akan hancur jika semua pihak merasa paling benar, sementara golongan kelompok lainnya merasa paling minoritas serta dirugikan. Harus ada “warning” dalam tatanan hidup bersama.
Jika tidak, maka bukan tidak mungkin bangsa ini akan mengalami kehancuran yang sama seperti terjadi di negara-negara timur tengah yang hancur bukan karena kelaparan, atau soal ekonomi. Namun karena piciknya para pemimpin agamanya bermain politik demi kekuasaan duniawi.
Sungguh sangat tidak elok rasanya, jika semua pihak menganggap sesamanya adalah ‘kafir’ dan harus beragama a, b, c, dengan pemaksaan. Kita semua harus mengenal arti kata “dakwah” itu sendiri, sebab konsep dakwah yang sejati adalah dakwah yang mengagungkan keberagaman tanpa paksaan. Untuk itu, marilah kita sebagai elemen berbangsa, kita sama-sama menjaga tatanan hidup dengan menghindari segala bentuk kebutuhan untuk memastikan ekslusivitas, namun menjadi masyarakat yang saling berangkulan satu dengan lainnya dalam perbedaan (Bhinneka Tunggal Ika).
Oleh: Abdy Busthan
***
Tulisan ini di ambil dari Buku:
Judul: Negara bukan Agama! Agama bukan Negara!
Penulis: Abdy Busthan
ISBN: 978-602-6487-05-6




 Apabila pendidikan di ibaratkan dengan sebuah mesin, maka makna apakah yang hendak dikandung oleh sebuah kebebasan? Jika, dunia pendidikan merupakan tempat bagi para pelaku-pelaku kebebasan, akankah ada suatu perubahan perilaku bagi seluruh oknum yang terlibat di dalamnya?
Apabila pendidikan di ibaratkan dengan sebuah mesin, maka makna apakah yang hendak dikandung oleh sebuah kebebasan? Jika, dunia pendidikan merupakan tempat bagi para pelaku-pelaku kebebasan, akankah ada suatu perubahan perilaku bagi seluruh oknum yang terlibat di dalamnya? 

 Dalam bentuk kajian apapun, hukum Syariat tetap tidak bisa diperkenankan untuk diberlakukan dalam tatanan kehidupan bangsa yang menjunjung prinsip Demokrasi-Konstitusional (Constitutional Democracy). Apalagi jika hukum agama tersebut harus dipaksakan untuk mengatur moral setiap individu melalui negara. Moral adalah urusan agama dari masing-masing individu. Negara sama sekali tidak berhak mengatur moral seseorang. Itu sebabnya, hukum negara dan hukum agama, mutlak tidak dapat digabungkan. Hukum agama bersifat absolut, sedangkan hukum negara bersifat dinamis-relatif yang sesuai dengan tuntutan zaman.
Dalam bentuk kajian apapun, hukum Syariat tetap tidak bisa diperkenankan untuk diberlakukan dalam tatanan kehidupan bangsa yang menjunjung prinsip Demokrasi-Konstitusional (Constitutional Democracy). Apalagi jika hukum agama tersebut harus dipaksakan untuk mengatur moral setiap individu melalui negara. Moral adalah urusan agama dari masing-masing individu. Negara sama sekali tidak berhak mengatur moral seseorang. Itu sebabnya, hukum negara dan hukum agama, mutlak tidak dapat digabungkan. Hukum agama bersifat absolut, sedangkan hukum negara bersifat dinamis-relatif yang sesuai dengan tuntutan zaman. Sesungguhnya dalam konstitusi Indonesia, hanya ada satu nomenklatur yang digunakan untuk menyatakan kesamaan dan kesetaraan, yaitu “warga negara” Indonesia. Artinya bahwa apapun bentuk status dan kedudukan sosial serta latarbelakang suku, agama, ras dan lain sebagainya, yang dimiliki oleh seseorang, maka kedudukannya sebagai warga negara juga “setara” dengan kedudukan orang-orang lain yang berada disekitarnya.
Sesungguhnya dalam konstitusi Indonesia, hanya ada satu nomenklatur yang digunakan untuk menyatakan kesamaan dan kesetaraan, yaitu “warga negara” Indonesia. Artinya bahwa apapun bentuk status dan kedudukan sosial serta latarbelakang suku, agama, ras dan lain sebagainya, yang dimiliki oleh seseorang, maka kedudukannya sebagai warga negara juga “setara” dengan kedudukan orang-orang lain yang berada disekitarnya.
 Ada ungkapan seperti ini: “dia itu orang kafir" ; "orang kafir itu tidak pantas menjadi pemimpin" ; "orang-orang kafir itu tidak akan masuk syurrga”... dan bla..bla...bla...lainnya
Ada ungkapan seperti ini: “dia itu orang kafir" ; "orang kafir itu tidak pantas menjadi pemimpin" ; "orang-orang kafir itu tidak akan masuk syurrga”... dan bla..bla...bla...lainnya
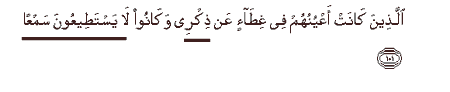
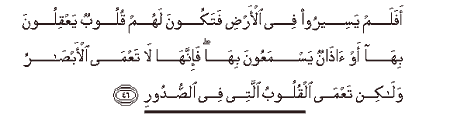
 Ada pertanyaan sederhana, apakah keyakinan kita terhadap sesuatu bisa menjawab segala hal yg tidak kita ketahui terlebih dahulu?
Ada pertanyaan sederhana, apakah keyakinan kita terhadap sesuatu bisa menjawab segala hal yg tidak kita ketahui terlebih dahulu?